PERSPEKTIF
Bangun Damai, Redakan Konflik
Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat hidup dalam keberagaman yang tak tertandingi. Namun, keberagaman bukan jaminan akan keharmonisan
TRIBUNBATAM.id - Indonesia adalah negara yang diberkahi kekayaan budaya, etnis, dan bahasa.
Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat hidup dalam keberagaman yang tak tertandingi. Namun, keberagaman bukan jaminan akan keharmonisan. Di banyak titik, perbedaan justru menjadi pemicu konflik.
Berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2023, terdapat lebih dari 70 kasus konflik sosial dalam lima tahun terakhir yang berkaitan dengan isu etnis, agama, dan identitas budaya.
Tidak sedikit dari konflik tersebut menimbulkan korban jiwa, pengungsian massal, hingga trauma psikologis berkepanjangan bagi komunitas terdampak. Fakta ini menunjukkan bahwa keberagaman Indonesia, yang selama ini dibanggakan, masih rentan terhadap friksi dan perpecahan jika tidak dikelola dengan baik
Pentingnya membahas isu ini terletak pada kenyataan bahwa konflik berbasis identitas bukan hanya memecah hubungan antarkelompok, tetapi juga mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan sosial. Pemahaman terhadap dinamika konflik, akar kekerasan, dan strategi membangun damai sangat krusial untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Konflik Dayak–Madura di Kalimantan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an adalah contoh nyata konflik etnis yang dipicu oleh berbagai ketimpangan dan
prasangka. Ketegangan antara dua kelompok ini dipicu oleh berbagai faktor: perbedaan budaya, dominasi ekonomi, hingga ketimpangan dalam representasi politik lokal.
Konflik di Sambas (1999) dan Sampit (2001) bukan hanya konflik horizontal, melainkan akibat tumpukan perbedaan budaya, dominasi ekonomi, serta representasi politik yang timpang.
Ribuan orang mengungsi dan hingga kini, hubungan sosial antaretnis masih dibayangi trauma.
Tidak hanya di Kalimantan, kasus di Papua juga menggambarkan dinamika serupa. Kerusuhan Wamena pada 2019 dipicu oleh hoaks bernuansa rasial.
Namun di balik itu, ada akumulasi kemarahan masyarakat Papua terhadap perlakuan diskriminatif yang mereka alami selama puluhan tahun. Rasa tidak dilibatkan, tidak didengarkan, dan tidak diberdayakan menjadi bahan bakar dari letupan kekerasan.
Di sini, kita melihat bagaimana cultural violence dan structural violence saling menopang.
Secara psikologis, konflik ini menunjukkan bahwa kekerasan muncul dari akumulasi ketimpangan dan narasi dominasi. Saat suatu kelompok merasa tidak
didengar atau tidak diakui, maka frustrasi akan berubah menjadi kemarahan kolektif.
Jika sistem sosial tidak menyediakan ruang partisipasi dan keadilan, maka konflik sulit dicegah. Sebagai penulis, saya melihat bahwa banyak konflik etnis di Indonesia tidak ditangani secara menyeluruh. Kita sering fokus pada pemadaman konflik (peacemaking), tetapi abai pada pembangunan damai jangka panjang (peacebuilding). Ini menyebabkan konflik mudah kambuh dan perdamaian bersifat
semu.
Di Indonesia, banyak inisiatif lokal menunjukkan semangat peacebuilding.
Misalnya, pasca kerusuhan Poso, berbagai komunitas lintas agama dan etnis membentuk forum dialog yang difasilitasi LSM dan tokoh masyarakat. Anak-anak dari latar belakang berbeda dilibatkan dalam program bersama mulai dari seni, olahraga, hingga kewirausahaan.
| Perdamaian Tak Buta Gender: Mencari Jalan Tengah atas Diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia |

|
|---|
| Merajut Ukhuwah Dalam Bingkai Dakwah |

|
|---|
| Berteman dalam Perbedaan: Pelajaran Toleransi Sejak Usia Dini |

|
|---|
| Desentralisasi dan Otonomi: Sebuah Mimpi Daerah untuk Lebih Mandiri |

|
|---|
| Belum Lima Detik, Antara Mitos dan Fakta Kesehatan |

|
|---|





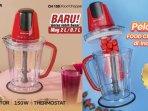


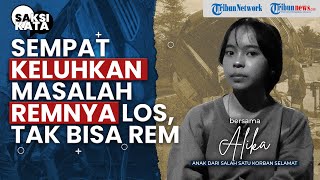





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.